Adik pulang dari sekolah. Baju putihnya berdebu macam semalam. Kasut rabaknya nampak selekeh. Wajahnya membayang lesu. Penatberjalan dua batu pulang dari sekolah. Adik muram macam semalam. "Apa halnya dek?" Tanya Azam pada adiknya.
"Cikgu tanya lagi tentang duit yuran. Adik kena berdiri di luar kelas tadi. Masa senaman, cikgu marah, adik tak ada t-shirt putih yang diminta sejak bulan lepas".
"Abang…adik malulah nak ke sekolah".
"Sudahlah dek. Nanti kita cakap lagi. Pergi mandi, sembahyang, lepas tu makan sama abang di dapur." Adik patuh. Dia melangkah longlai. Kasut rabak macam mulut buaya itu ditinggalkan dengan mudah. Diletaknya baik-baik di clah dinding rumah yang robek. Tak lama kemudian terdengar cebur-cebur air telaga di belakang rumah. Adik mandi. Kemudian adik pakai kain pelekat usang peninggalan ayah dan hampar sejadah daun mengkuang anyaman ibu.
"Allahu Akbar". Suara Adik bertakbir. Adik sembahyang dengan tenang.
Azam ke belakang. Dibukanya periuk nasi yang telh dimasak oleh ibu sebelum turun ke kebun. Tinggal separuh lagi. Hanya dia dan adik yang belum makan. Kak Milah dah makan sama ibu sebelum turun ke kebun.
Mereka empat beranak sajalah yag tinggal di rumah sobek peninggalan arwah ayah. Ayah meninggal sebulan yang lalu setelah dua tahun terlantar sakit dala perut. Sejak itu, ibulah yang mencari nafkah buat mereka. Azam berusia sepuluh tahun. Kak Milah dua belas tahun dan adik baru dalam darjah dua.
"Bang…dah siap."
"Cikgu tanya lagi tentang duit yuran. Adik kena berdiri di luar kelas tadi. Masa senaman, cikgu marah, adik tak ada t-shirt putih yang diminta sejak bulan lepas".
"Abang…adik malulah nak ke sekolah".
"Sudahlah dek. Nanti kita cakap lagi. Pergi mandi, sembahyang, lepas tu makan sama abang di dapur." Adik patuh. Dia melangkah longlai. Kasut rabak macam mulut buaya itu ditinggalkan dengan mudah. Diletaknya baik-baik di clah dinding rumah yang robek. Tak lama kemudian terdengar cebur-cebur air telaga di belakang rumah. Adik mandi. Kemudian adik pakai kain pelekat usang peninggalan ayah dan hampar sejadah daun mengkuang anyaman ibu.
"Allahu Akbar". Suara Adik bertakbir. Adik sembahyang dengan tenang.
Azam ke belakang. Dibukanya periuk nasi yang telh dimasak oleh ibu sebelum turun ke kebun. Tinggal separuh lagi. Hanya dia dan adik yang belum makan. Kak Milah dah makan sama ibu sebelum turun ke kebun.
Mereka empat beranak sajalah yag tinggal di rumah sobek peninggalan arwah ayah. Ayah meninggal sebulan yang lalu setelah dua tahun terlantar sakit dala perut. Sejak itu, ibulah yang mencari nafkah buat mereka. Azam berusia sepuluh tahun. Kak Milah dua belas tahun dan adik baru dalam darjah dua.
"Bang…dah siap."
"Ha…mari makan. Lauk macam biasa dek."
"Bang …adik malulah nak ke sekolah. Malu dengan cikgu, malu dengan kawan-kawan." Adik bersuara menyambung cakapnya tadi.
"Sabarlah dek. Teruskan belajar. Nanti emak dapat duit boleh beli semuanya. Adik mesti terus belajar. Abang cacat, Kak Milah terpaksa tolong emak, adik saja harapan kami."
Mata adik merenung lembut pada mata abangnya. Direnung muka Azam yang cacat. Direnungnya kaki Azam yang pincang dan tangannya yang kudung sebelah. Azam abangnya…abang yang cacat sejak dilahirkan.
"Abang, jangan cakap macam tu. Abang, Kak Milah, emak semua susah. Dik nak tolong…adik nak berhenti sekolah, nak tolong emak di kebun."
"Jangan! Adik ingat tak pesan ayah dulu? Kan ayah minta adik terus belajar. Walau apa pun terjadi adik mesti belajar."
Wajah ayah yang kurus – cengkung menjelang kematiannya kembali tertayang di mata Azam. Masih basah dalam ingatannya bagaimana ayah mengusap mukanya yang cacat. Ayah kuat ibadah. Dalam sakitnya dia tetap sembahyang. Sembahyng wajib dan sunatnya dikerjakan sambil berbaring. Wirid ayah sentiasa di bibir. Badan ayah sakit tapi hatinya tidak. Doanya tetap panjang. Tapi nasib ayah memang malang. Hidup sebatang kara. Ayah tiada saudara mara. Ayah cuma pendatang dari seberang. Harta tiada, saudara mara tiada.
"Azam…jaga adikmu baik-baik. Bila emak kau ke kebun jaga rumah. Tengok-tengokkan makan minum adik kau. Kak Milah Bantu emak. Tinggal kau sorang saja nanti di rumah." Begitu pesan ayah.
"Ayah?"
"Ayah akan pergi Zam…"
Pesan ayah lagi: "Jaga sembahyang adik kau, jaga makan minumya dan tegur salah silapnya…" Azam tunduk. Air mata mengalir dari pipinya yang menggerutu.
"Engkau dengar Zam?"
"Dengar ayah." Sahutnya perlahan.
Wajah adik memang mirip wajah ayah. Azam perhatikan adiknya menyuap nasi. Penuh selera walaupun Cuma berkuah kicap. Berlauk ikan masin. Melihat adik menyuap nasi, Azam teringat ayah…sejak dua tahun sakit menjelang kematiannya ayah tak selera makan lagi. Suapanibu selalu ditolaknya. Kalau dipaksa-paksa ayah akan muntah.
"Bang, kenapa tak makan?
"Makanlh asampai kenyang, nanti abang makan lebihnya." Sahut Azam lebut. Begitulah selalunya. Adik dah faham benar sikap Azam. Azam tetap akan mengalah. Nasi yang sedikt akan didahulukannya buat adik. Biar Azam makan sedikit asal adik kenyang.
Lepas makan Azam dan adik menyapu du laman rumah. Biar rumah kita buruk asal bersih, begitu pesan arwah ayah mereka.
Tak lama kemudian Kak Milah dan ibu pulang dari kebun. Ibu seperti biasa, tetap senyum melihat mereka. Dialah ibu yang sabar. Pewaris derita ayah. (Bersambung...(",)
"Bang …adik malulah nak ke sekolah. Malu dengan cikgu, malu dengan kawan-kawan." Adik bersuara menyambung cakapnya tadi.
"Sabarlah dek. Teruskan belajar. Nanti emak dapat duit boleh beli semuanya. Adik mesti terus belajar. Abang cacat, Kak Milah terpaksa tolong emak, adik saja harapan kami."
Mata adik merenung lembut pada mata abangnya. Direnung muka Azam yang cacat. Direnungnya kaki Azam yang pincang dan tangannya yang kudung sebelah. Azam abangnya…abang yang cacat sejak dilahirkan.
"Abang, jangan cakap macam tu. Abang, Kak Milah, emak semua susah. Dik nak tolong…adik nak berhenti sekolah, nak tolong emak di kebun."
"Jangan! Adik ingat tak pesan ayah dulu? Kan ayah minta adik terus belajar. Walau apa pun terjadi adik mesti belajar."
Wajah ayah yang kurus – cengkung menjelang kematiannya kembali tertayang di mata Azam. Masih basah dalam ingatannya bagaimana ayah mengusap mukanya yang cacat. Ayah kuat ibadah. Dalam sakitnya dia tetap sembahyang. Sembahyng wajib dan sunatnya dikerjakan sambil berbaring. Wirid ayah sentiasa di bibir. Badan ayah sakit tapi hatinya tidak. Doanya tetap panjang. Tapi nasib ayah memang malang. Hidup sebatang kara. Ayah tiada saudara mara. Ayah cuma pendatang dari seberang. Harta tiada, saudara mara tiada.
"Azam…jaga adikmu baik-baik. Bila emak kau ke kebun jaga rumah. Tengok-tengokkan makan minum adik kau. Kak Milah Bantu emak. Tinggal kau sorang saja nanti di rumah." Begitu pesan ayah.
"Ayah?"
"Ayah akan pergi Zam…"
Pesan ayah lagi: "Jaga sembahyang adik kau, jaga makan minumya dan tegur salah silapnya…" Azam tunduk. Air mata mengalir dari pipinya yang menggerutu.
"Engkau dengar Zam?"
"Dengar ayah." Sahutnya perlahan.
Wajah adik memang mirip wajah ayah. Azam perhatikan adiknya menyuap nasi. Penuh selera walaupun Cuma berkuah kicap. Berlauk ikan masin. Melihat adik menyuap nasi, Azam teringat ayah…sejak dua tahun sakit menjelang kematiannya ayah tak selera makan lagi. Suapanibu selalu ditolaknya. Kalau dipaksa-paksa ayah akan muntah.
"Bang, kenapa tak makan?
"Makanlh asampai kenyang, nanti abang makan lebihnya." Sahut Azam lebut. Begitulah selalunya. Adik dah faham benar sikap Azam. Azam tetap akan mengalah. Nasi yang sedikt akan didahulukannya buat adik. Biar Azam makan sedikit asal adik kenyang.
Lepas makan Azam dan adik menyapu du laman rumah. Biar rumah kita buruk asal bersih, begitu pesan arwah ayah mereka.
Tak lama kemudian Kak Milah dan ibu pulang dari kebun. Ibu seperti biasa, tetap senyum melihat mereka. Dialah ibu yang sabar. Pewaris derita ayah. (Bersambung...(",)







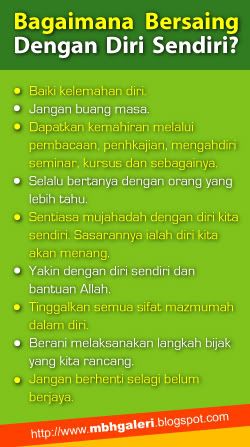

No comments:
Post a Comment